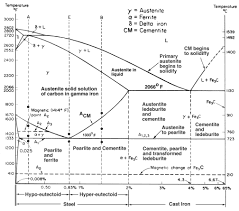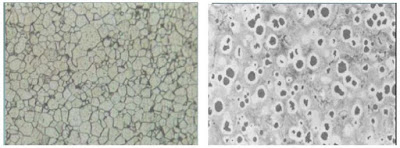Pemilihan dan desain material untuk aplikasi pada temperatur
tinggi khususnya untuk menghindari fenomena creep
harus mengacu pada permasalahan utama yang terjadi pada material jika
terkena temperatur tinggi, yaitu pada temperatur tinggi atom akan bergerak
sangat cepat akibat adanya proses difusi dan mengakibatkan ketidakstablian
mikrostruktur yang berdampak pada sifat mekanik material tersebut. Pada logam
dan keramik pemilihan dan desain materialnya harus mengacu pada aspek-aspek
tertentu, yaitu[1, 3]:
1. Pemllihan material untuk menghindari fenomena dislocation creep
· Memilih material logam ataupun keramik yang
memiliki temperatur leleh yang tinggi (Tm)
· Melakukan pemaduan (alloying) untuk membentuk solid
solution dan atau presipitat yang stabil pada temperatur tertentu untuk
memaksimalkan dalam menghalangi pergerakan dislokasi
· Memilih material (keramik) yang memiliki
regangan kisi yang besar seperti beberapa unsur dalam bentuk oksida atau
silika, silikon karbida, dan silikon nitride
2.
Pemilihan material untuk menghindari fenomena diffusional crep
· Memilih material logam ataupun keramik yang
memiliki temperatur leleh yang tinggi (Tm)
·
Menggunakan material dengan butir yang besar
· Mengatur kehomogenan presipitat pada batas butir
untuk meminimalkan proses grain boundary
sliding
Proses creep pada logam terjadi di T > 0.3 – 0.4 Tm[3], dan
pada keramik terjadi pada kisaran T > 0.4 – 0.5 Tm[3]. Oleh
karena itu dibutuhkan material dengan temperatur leleh (Tm) yang tinggi.
Semakin tinggi Tm suatu material maka material tersebut sulit untuk mengalami
fenomena creep karena temperaturnya
tidak masuk dalam kisaran/range terjadinya
fenomena creep.
Gambar 1.
Jenis material beserta temperatru lelehnya[5]
Gambar 2.
Kekuatan creep berbagai jenis
material pada suhu 9500C[5]
Selanjutnya
yaitu material dengan butir yang besar memiliki ketahanan creep yang baik. Karena degnan semakin besarnya butir pada suatu
material maka akan mengurangi batas butir yang berdampak pada berkurangnya laju
difusi, karena diperlambat dengan sedikitnya batas butir. Selain itu batas
butir yang sedikit akan meminimalkan proses grain
boundary sliding. Sehingga material single
crystal merupakan piihan yang terbaik untuk mengurangi proses creep.
Gambar 3.
Perbandingan antara besar butir terhadap proses creep[1]
Dan yang terakhir adalah dengan merekayasa
mikrostruktur dengan cara penambahan unsur paduan agar didapatkan material yang
tahan terhadap creep. Tujuan utama
dari penambahan unsur paduan ini yaitu untuk memodifikasi fasa matriks agar
lebih stabil pada temperatur tinggi dan untuk menghasilkan presipitat dan solid solution strengthening sehingga
menyulitkan pergerakan dislokasi dan tidak terjadi deformasi pada material.
Unsur-unsur paduan yang ditambahkan antara lain[4]:
· Ni (hingga 70%): Memberikan kekuatan dan
ketangguhan pada matriks, menjadikan matriks memiliki fasa austenite yang
stabil pada temperatur tinggi dan untuk menghindari terbentuknya fasa gamma
yang getas, meningkatkan ketahanan oksidasi, karburisasi, nitridisasi dan
meningkatkan resistansi terhadap thermal
fatigue.
· Cr (10 – 30%): Memberikan ketahanan terhadap
oksidasi dan sulfidasi, berikatan dengan karbon membentuk CrC yang memiliki
ketahanan creep yang baik dan
meningkatkan UTS pada temperatur tinggi. Namun Cr dapat membentuk fasa ferrite
yang dapat berubah menjadi fasa gamma yang getas sehingga harus diatur
sedemikian rupa.
· C (0.20 – 0.75%): Membentuk karbida dengan
unsur-unsur pembentuk karbida sehingga meningkatkan ketahanan creep dan menambah UTS dalam temperatur
tinggi
· Mo, Zr, Ti, N, dan W: Merupakan unsur-unsur
pembentuk karbida dan presipitat [Ni3(Al, Ti)] sehingga dapat
menahan laju creep dan pergerakan
dislokasi dan presipitat yang tersebar merata dan homogen di daerah batas butir
dapat mengurangi resiko terjadinya grain
boundary sliding
Sedangkan pada material polimer,
pemilihan dan desain material yang dilakukan untuk mengurangi proses creep yaitu dengan cara memilih material
dengan derajat cross-lingking yang
tinggi, karena Tg berbanding lurus dengan banyaknya cross-linking sehingga akan lebih tahan creep. Kemudian mengurangi berat molekul polimer tersebut, karena
dengan semakin tingginya berat molekul maka viskositas akan semakin meningkat
sehingga akan lebih mudah untuk creep.
Serta memilih material polimer yang mikrostrukturnya semikristalin untuk
menambah ketahanan creep. Selain itu
material polimer bisa ditambahkan dengan serbuk silika yang digunakan sebagai filler, dan bisa ditambahkan serat-serat
fiber sehingga beban yang diberikan akan dibawa oleh fiber tersebut sehingga sifat mekanik dan ketahanan creep-nya meningkat.
Tabel 1 Range temperatur dan jenis material yang
digunakan[3]
Contoh material yang digunakan untuk aplikasi ketahanan creep pada temperatur tinggi adalah Nickel-Base Alloy yang dapat bertahan
hingga suhu 10390C. Material tersebut memiliki sifat yang baik
karena terdiri dari matriks berupa austenitic
FCC gamma yang dapat melarutkan unsur=unsur seperti Co, Fe, Mo, Cr, Ti yang
membentuk solid solution strengthening serta
membentuk presipitat berupa gamma prime berupa
Ni3(Al, Ti) yang dapat menghalangi pergerakan dislokasi sehingga
sulit terjadi creep.
Silahkan Download Artikel di atas Dalam Bentuk:
DOC | PDF
Daftar Pustaka
[1] Callister, William D.
2007. Materials Science and Engineering:
An Introduction Seventh Edition. USA: John Wiley & Sons, Inc.
[2] ASM Handbook Volume 20: Materials Selection and Design. ASM
International.
[3] Ashby, Michael F. dan
David R. H. Jones. 2005. Engineering
Materials I: An Introduction to Properties, Applications and Design.
Elsevier Butterworth – Heinemann.
[4] Suharno, Bambang. 2013. Diktat Kuliah Baja Khusus dan Paduan Super.
Departemen Teknik Metalurgi dan Material FTUI.
[6] Sofyan, Nofrijon. 2012. Diktat Kuliah Metalurgi Fisik 1.
Departemen Teknik Metalurgi dan Material FTUI.